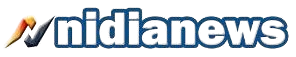Oleh Adi Suputra
Akademisi Universitas Pertiba (Uniper)
Di negeri yang sering disebut “Konoha” sebuah metafora bagi negara yang katanya kuat dan beradab segala hal yang berbau swasta selalu dihadapi dengan regulasi yang kaku, berliku, dan condong tidak memihak.
Setiap kali membicarakan kebijakan publik, kita seolah mengurai benang kusut yang tak pernah selesai. Regulasi hadir bukan untuk memecahkan masalah, tapi seakan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Kebijakan publik yang idealnya berpijak pada UUD 1945 alinea ke-4 cita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia kini sering kali tereduksi menjadi instrumen kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.
Arah kebijakan pendidikan, ekonomi, dan sosial tampak lebih banyak mengikuti arah angin kekuasaan daripada arah nurani konstitusi.
- Ketika Negara Gagal Menjadi Wasit
Secara teori kebijakan publik, negara idealnya berperan sebagai “wasit” yang menjamin keadilan dan keseimbangan antara sektor publik dan swasta. Namun dalam praktiknya, negara justru sering menjadi “pemain” yang memihak salah satu tim di lapangan. Hal ini menimbulkan market distortion dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga ekonomi lokal.
Regulasi yang terlalu sentralistik membuat sektor swasta termasuk perguruan tinggi swasta, koperasi, dan usaha masyarakat harus berjuang di tengah birokrasi yang tidak efisien. Padahal teori pembangunan modern (Todaro, Sen) menekankan: kemajuan negara bergantung pada synergy between state and civil society, bukan dominasi satu pihak.
- Akademisi sebagai Penjaga Rasionalitas Bangsa
Dalam situasi seperti ini, akademisi dan dunia pendidikan menjadi tumpuan terakhir rasionalitas bangsa. Seorang dosen bukan hanya pengajar, tapi penjaga kesadaran kritis masyarakat.Namun, mereka sering dibiarkan berjuang sendiri, di bawah tekanan ekonomi, politik, dan birokrasi pendidikan yang tak berpihak.
Di ruang kelas, para dosen dan mahasiswa menjadi aktor perubahan tempat terakhir di mana bangsa ini masih belajar berpikir jernih. Mereka tidak boleh menyerah pada pragmatisme politik yang mengajarkan bahwa suara rakyat bisa dibeli, dan kebijakan bisa diatur sesuai kepentingan. Dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya budi pekerti, bukan sekadar alat pencetak tenaga kerja.Itulah nilai yang kini terancam hilang.
- Politik Uang dan Apatisme Struktural
Masyarakat di akar rumput kini dibentuk untuk tidak peduli.Budaya money politics telah menumpulkan daya kritis rakyat, membuat mereka memilih wakil rakyat bukan karena visi, tetapi karena amplop. Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai symbolic violence kekuasaan yang menindas tanpa disadari karena telah menjadi bagian dari budaya.
Akibatnya, yang duduk di kursi kekuasaan sering kali bukan mereka yang memahami UUD 1945, melainkan mereka yang sekadar menghafal jargon pembangunan tanpa makna. Dampaknya bukan hanya pada politik, tapi juga pada moral sosial: rakyat kehilangan kepercayaan, dan pendidikan kehilangan arah etik.
- Ketika Konstitusi Ditinggalkan di Meja Retorika
Secara hukum, UUD 1945 Alinea Ke-4 adalah roh konstitusional yang menjiwai seluruh kebijakan publik. Namun, roh itu kini seakan tinggal teks yang dibacakan saat upacara kenegaraan tanpa makna praksis. Kebijakan dibuat bukan untuk “melindungi dan mencerdaskan”, tapi untuk “mengatur dan menguasai”.
Inilah bentuk deviasi konstitusional yang berbahaya ketika hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan alat justifikasi kepentingan. Negara hukum (rechtstaat) berubah menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Dalam konteks ini, tugas akademisi hukum dan sosial bukan hanya mengajar pasal, tapi membangkitkan kesadaran bahwa konstitusi adalah moral hidup berbangsa, bukan dokumen mati.
- Takdir Akademisi adalah Perjuangan
Menjadi akademisi berarti menerima takdir eksistensial untuk berhadapan dengan tantangan. Dalam pandangan eksistensialisme (Sartre), manusia ditentukan oleh pilihannya. Dan pilihan akademisi adalah berpihak pada kebenaran meski kebenaran itu sering kali sepi.
Akademisi adalah penjaga “ruh bangsa” yang menolak tunduk pada apatisme. Sebab tanpa keberanian berpikir dan berbicara, universitas akan kehilangan jiwanya, dan bangsa kehilangan nuraninya.
Harapan di Tengah Kekusutan
Bangsa ini mungkin sedang mengurai benang kusut yang panjang kebijakan yang tak berpihak, politik uang yang membodohkan, dan generasi muda yang mulai lelah berharap. Namun, dari ruang-ruang kuliah yang sederhana, masih ada nyala kecil yang terus dijaga: nyala akal sehat, nyala kejujuran, nyala harapan akan perubahan.
Tugas kita para akademisi, dosen, dan mahasiswa bukan hanya mengkritik, tetapi membangun kembali kesadaran bahwa peradaban tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari pengetahuan yang berani melawan kebodohan dan ketidakadilan.
Di negeri Konoha, mungkin benang kusut belum terurai, tapi selagi ada yang mau berpikir, menulis,dan mengajar dengan hati masih ada harapan bangsa ini akan menemukan jalannya kembali.